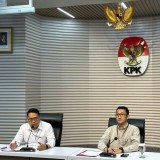TIMES JAMBI, JAKARTA – Pertanyaan seputar hukum memakan buah atau sayur yang berulat kerap muncul di tengah masyarakat. Dalam literatur fiqih, ulama membahas persoalan ini secara detail, termasuk dalam kitab I’anatut Thalibin karya Sayyid Abu Bakar Syatha Ad-Dimyathi.
Dalam kitab tersebut, beliau menulis:
ويحل أكل دود مأكول معه، ولا يجب غسل نحو الفم منه...
(قوله : ويحل أكل دود مأكول) أي كدود التفاح وسائر الفواكه ودود الخل، فميتته وإن كانت نجسة لكنها لا تنجس ما ذكر، لعسر الاحتراز عنه. وحل أكله لعسر تمييزه.
(قوله: ولا يجب غسل نحو الفم منه) أي لأنه لا يتنجس به.
Artinya:
"Dan halal memakan ulat yang terdapat bersama makanan yang dimakan, dan tidak wajib membasuh (membersihkan) mulut dan semisalnya darinya. Maksudnya seperti ulat pada apel dan seluruh buah-buahan serta ulat pada cuka. Bangkainya meskipun najis, namun tidak menajiskan apa yang disebutkan tadi karena sulit menghindarinya. Dan halal memakannya karena sulit memisahkannya. Adapun mulut tidak wajib dibasuh karena tidak menjadi najis karenanya." (I’anatut Thalibin, juz 1, hal. 109).
Dari sini terdapat pendapat bahwa ulat yang muncul di dalam buah atau cairan tertentu tidak otomatis membuat makanan itu najis. Alasannya, manusia sangat sulit menghindari ulat kecil yang tumbuh alami di dalam buah atau sayuran.
Namun, ulama dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah memberi penjelasan lebih rinci dengan menetapkan syarat tertentu. Dalam Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah disebutkan:
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَحِل أَكْل الدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ فِي طَعَامٍ كَخَلٍّ وَفَاكِهَةٍ بِثَلاَثِ شَرَائِطَ:
الأُْولَى: - أَنْ يُؤْكَل مَعَ الطَّعَامِ، حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا، فَإِنْ أُكِل مُنْفَرِدًا لَمْ يَحِل.
الثَّانِيَةُ: - أَلاَّ يُنْقَل مُنْفَرِدًا، فَإِنْ نُقِل مُنْفَرِدًا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ. وَهَاتَانِ الشَّرِيطَتَانِ مَنْظُورٌ فِيهِمَا أَيْضًا إِلَى مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ.
الثَّالِثَةُ: - أَلاَّ يُغَيِّرَ طَعْمَ الطَّعَامِ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ إِنْ كَانَ مَائِعًا، فَإِنْ غَيَّرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ وَلاَ شُرْبُهُ، لِنَجَاسَتِهِ حِينَئِذٍ.
Artinya:
"Ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah berpendapat: Halal memakan ulat yang muncul dalam makanan seperti pada cuka dan buah-buahan, dengan tiga syarat: Pertama, dimakan bersama makanan itu baik ulatnya hidup maupun mati. Jika dimakan terpisah, maka tidak halal. Kedua, tidak dipindahkan secara terpisah. Jika dipindahkan, maka tidak boleh dimakan. Ketiga, ulat tidak boleh mengubah rasa, warna, atau baunya jika makanan tersebut berupa cairan. Jika sampai berubah, maka tidak boleh dimakan atau diminum karena dianggap najis." (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, juz 5, hal. 143).
Tiga syarat tersebut mempertegas bahwa keberadaan ulat dalam buah atau sayur tidak otomatis menjadikan makanan itu haram. Halalnya bergantung pada konteks: apakah dimakan bersama makanan asalnya, tidak dipisahkan, dan tidak mengubah sifat makanan.
Dengan demikian, umat Islam tidak perlu khawatir berlebihan jika mendapati buah atau sayur yang ternyata berulat. Selama sesuai dengan ketentuan ulama, memakannya tetap diperbolehkan.
Di sisi lain, sebagian orang tetap memilih membuang bagian yang berulat demi kebersihan dan kenyamanan.
Hal itu juga tidak bertentangan dengan fiqih, karena hukum asalnya memberi kelonggaran, sementara praktik sehari-hari bisa mengikuti preferensi pribadi dalam menjaga kesehatan dan selera makan. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Buah Berulat Masih Bisa Dimakan? Simak Hukum Fiqihnya
| Pewarta | : Yusuf Arifai |
| Editor | : Ronny Wicaksono |